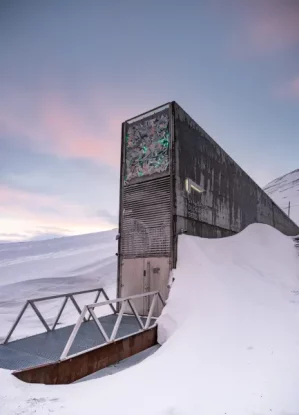Kalimantan Timur adalah provinsi pertama di Indonesia yang menjalankan program kemitraan Forest Carbon Partnership Facility – Carbon Fund (FCPF-CF) dari Bank Dunia. Program ini melibatkan mekanisme pembayaran berbasis kinerja (Result-Based Payment/RBP) atas keberhasilan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+). Program pengurangan emisi berbasis yurisdiksi ini dijalankan di Kalimantan Timur sejak November 2021 hingga Desember 2025 dengan total nilai mencapai 110 juta dolar AS atau sekitar Rp1,8 triliun.
Program FCPF-CF ini memunculkan gagasan agar mekanisme REDD+ di Kalimantan Timur juga bisa berjalan dalam skema perdagangan karbon berbasis pasar. Perdagangan karbon didasarkan pada pemikiran bahwa perusahaan dan pemerintah perlu melakukan lebih banyak hal untuk mencapai target pengurangan emisi karbon dunia, salah satunya dengan cara membayar pengurangan emisi karbon yang terjadi di tempat lain, dalam hal ini misalnya di Kalimantan Timur, dalam sebuah sistem ekonomi global. REDD+ memungkinkan dikeluarkannya kredit karbon yang menghitung jumlah emisi karbon yang terhindari atau terserap melalui “deforestasi yang dihindari”–dengan tidak menebangi pohon, atau dengan restorasi hutan. Dengan demikian, kredit karbon dari Kalimantan Timur dapat diperdagangkan dalam pasar karbon.
Dampak Sosial dan Tantangan Keadilan
Program REDD+ di Kalimantan Timur itu telah membuat Indonesia menjadi negara pertama di Asia Pasifik yang menerima kompensasi karbon berbasis kinerja di skala provinsi. Salah satu pembelajaran penting dari program REDD+ ini adalah dampaknya terhadap komunitas lokal dan masyarakat adat.
“Kaltim (Kalimantan Timur) menjalankan program kemitraan karbon hutan dengan Bank Dunia itu hingga akhir 2025 dan kita banyak menimba pengalaman. Banyak ternyata komunitas lokal dan masyarakat adat yang merasa sistem pendistribusian manfaat masih perlu ditingkatkan. Ini satu masukan berharga bagi program dan kita harus terbuka untuk menerimanya. Mengapa? Karena program ini bagi Kaltim, dan bahkan untuk Indonesia, merupakan satu pengalaman pertama. Kaltim berangkat dari nol untuk melaksanakan itu semua,” tutur Profesor Daddy Ruhiyat, Ketua Harian Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Kalimantan Timur.
Pemandangan udara Desa Buluq Sen, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Foto oleh Nanang Sujana/CIFOR.
Tidak hanya di Kalimantan Timur, berbagai kegiatan pengurangan emisi di seluruh dunia juga telah menghasilkan kritik dan saran untuk perbaikan di masa depan. Beberapa proyek dituding telah melebih-lebihkan dampak iklimnya, sementara yang lain gagal menegakkan dan menghormati hak-hak komunitas lokal dan masyarakat adat yang bergantung pada hutan yang harus dilindungi itu. Kepedulian banyak pihak atas dampak sosial dan lingkungan dari berbagai proyek tersebut telah memicu upaya menuju karbon integritas tinggi. Dalam konsep karbon integritas tinggi, kredit karbon harus memenuhi standar lingkungan dan sosial yang ketat agar dapat berkontribusi secara signifikan terhadap upaya menahan laju krisis iklim global.
Membangun Pemahaman tentang Karbon Integritas Tinggi
Pada Juni lalu, Center for International Forestry Research and World Agroforestry (CIFOR-ICRAF) bersama DDPI Kalimantan Timur mengadakan lokakarya tentang penurunan emisi gas rumah kaca (“karbon”), berjudul “Karbon Integritas Tinggi” di Samarinda, ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, dan Tenggarong, ibu kota Kutai Kartanegara—salah satu kabupaten di Kalimantan Timur. Sebagian tujuan dari lokakarya ini adalah mengidentifikasi kesenjangan kapasitas terkait REDD+ dan konsep karbon berintegritas tinggi serta mengidentifikasi pemahaman dan kapasitas yang perlu dikembangkan sehingga Kaltim mampu menghasilkan dan memasok kredit karbon berintegritas tinggi.
Dua lokakarya itu menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah hingga masyarakat lokal. Dalam lokakarya tersebut, para peneliti CIFOR-ICRAF berusaha memahami seberapa dalam pemahaman mereka soal REDD+ dan pengurangan emisi karbon dan seberapa besar kebutuhan atas aspek-aspek tertentu dalam menghasilkan penurunan emisi karbon integritas tinggi.
Sebelumnya, sudah banyak acara lokakarya, pelatihan, dan diskusi di Kalimantan Timur yang membahas isu-isu terkait proyek REDD+ seperti perhitungan pengurangan emisi dan keadilan dalam pembagian manfaat. “Saya berpikir bahwa pemahaman tentang pengurangan emisi akan tinggi dan aspek keadilan akan kurang dipahami. Namun, peserta lokakarya menilai pemahaman tentang aspek pengurangan emisi juga sebagian besar sedang dan rendah,” kata Moira Moeliono, Mitra Senior CIFOR-ICRAF.
Kesenjangan Pengetahuan dan Tantangan Sosial di Lapangan
Stibniati Atmadja, Ilmuwan CIFOR-ICRAF, mengatakan dirinya menjumpai dua jenis kelompok masyarakat yang berbeda dalam lokakarya tersebut. “Satu yang mengerti tentang REDD+ dan pengurangan emisi karbon, dan satu yang tidak terlalu mengerti. Yang mengerti tentang REDD+ itu yang kebanyakan berada di Samarinda. Mereka ikut serta dengan pembentukan dan pengembangan program REDD+ di Kalimantan Timur,” kata Atmadja. Namun, masih banyak juga pihak di Samarinda memiliki pengertian tentang REDD+ maupun soal pasar karbon yang bervariasi, terutama dari lembaga yang tidak terkait lingkungan atau kehutanan, tapi terkait ekonomi atau sosial. Muhammad Risman, Pekerja Sosial Ahli Pertama di Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur, adalah salah satunya. Risman mengatakan ini adanya pertama kalinya ia mengikuti kegiatan lokakarya terkait karbon semacam ini. “Untuk kegiatan ini, saya baru pertama kali ikut dan sangat-sangat tertarik,” katanya.
Berbeda dengan pengetahuan para pihak di tingkat provinsi, pemahaman peserta lokakarya di tingkat kabupaten soal pasar karbon sangat rendah. “Secara jujur saya harus sampaikan bahwa jika lokakarya itu dilakukan di tingkat provinsi, maka respons dari para pihak di tingkat provinsi itu, karena memang mereka telah terlibat lama sekali dalam proyek karbon itu, mereka memberikan informasi mencerminkan pemahaman yang baik. Tapi ketika itu dilakukan di tingkat kabupaten, pemahaman mereka masih terbatas. Sebagai contoh kemarin kita lakukan di Kabupaten Kutai Kartanegara, tercermin di situ bahwa perlu sosialisasi yang lebih luas agar dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terkait proyek karbon ini,” jelas Ruhiyat.

Marni dan Lisnawati, dua ibu rumah tangga dari Desa Sepatin di Kutai Kartanegara, adalah contohnya. Mereka tampak gelagapan saat ditanya soal proyek karbon. “Saya belum begitu banyak memahami, sih, karbon itu apa,” kata Marni. “Cuma sebagian tadi ada dikaitkan dengan kayu.” Senada dengan Marni, Lisnawati juga mengaku kaget karena dalam lokakarya itu mendapat pertanyaan soal perdagangan karbon. “Tinggi gitu pertanyaannya. Jadi kami enggak terlalu memahami,” ucapnya. Moeliono mengungkapkan, “Pengetahuan dasar tentang kenapa mereka harus pelihara hutan, dan kenapa ada yang mau bayar kalau [hutan mereka] tidak ditebang, itu belum dipahami hubungannya dengan perubahan iklim. Pemahaman itu perlu dimantapkan sebelum kita bisa bicara tentang hal-hal seperti REDD+ dan pasar karbon.”
Atmadja mengamati perempuan jarang mengikuti sosialisasi dan peningkatan pemahaman mengenai karbon karena hambatan norma sosial terkait gender. “Kenapa ada kesenjangan gender? Asumsinya, mengundang perempuan atau laki-laki sama saja, tetapi di desa, jaringan sosial mereka mempengaruhi arus informasi. Info yang diberikan ke bapak-bapak belum tentu akan menjangkau ke kalangan ibu-ibu, dan sebaliknya. Yang paling sering diundang lokakarya adalah para kades (kepala desa) dan aparat desa tertentu, mengingat jabatan atau posisi tersebut rata-rata dipegang oleh laki-laki, sedangkan keterwakilan wanita masih perlu diperkuat lagi. Di lingkup desa pun sama – kepala rumah tangga kebanyakan pria, dan merekalah yang sering diundang rapat desa. Itu satu. Yang kedua adalah mobilitas. Tanggung jawab mengurus rumah tangga lebih dibebankan ke wanita: urus anak, cuci baju, masak, membersihkan rumah, itu pekerjaan yang terus-menerus – tidak mudah ditinggal lama dan tidak bisa dilakukan lewat Zoom. Sementara untuk mengikuti acara, misalnya kegiatan lokakarya sehari penuh di kota kabupaten, wanita sungkan pergi kalau suami tidak membantu mengambil alih tugas rumah tangga wanita,” ujar Atmadja.
Membangun Pasar Karbon Indonesia yang Berintegritas dan Adil
Temuan kesenjangan pemahaman dan kapasitas para pemangku kepentingan di Kalimantan Timur soal karbon itu makin menegaskan pentingnya penerapan konsep karbon integritas tinggi di sana. Ruhiyat menilai peningkatan pemahaman tentang karbon integritas tinggi ini “sangat penting dan relevan dengan kebutuhan” di Kalimantan Timur. “Terutama untuk mendukung pemerintah Indonesia menjadi pemasok kredit karbon berintegritas tinggi, yang muaranya itu berkontribusi pada tujuan iklim global dan kesejahteraan masyarakat lokal,” katanya.
Deden Djaenudin, peneliti dari Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkuler BRIN, juga menilai peningkatan pemahaman tentang konsep karbon integritas tinggi ini penting untuk menyongsong masa depan pasar karbon di Kalimantan Timur. “Karena sudah banyak orang yang datang ke Kalimantan Timur untuk mencari lokasi-lokasi yang memang cocok untuk pengembangan perdagangan karbon ini,” ujar Deden.
Moeliono dan Atmadja menegaskan pentingnya aspek keadilan sosial dalam pasar kredit karbon yang sedang dikembangkan di Indonesia saat ini. “Meskipun hutan itu dikuasai negara, tapi banyak orang yang tinggal di situ dan pada akhirnya masyarakatlah yang memegang peran penting untuk bisa melindungi hutan. Mereka yang paling rentan dan, di satu pihak, juga paling bergantung pada sumber daya hutan itu untuk penghidupannya. Jadi masalah keadilan harus jadi perhatian Utama, agar pengelolaan ini tidak mengorbankan sumber penghidupan mereka,” kata Moeliono seraya menggarisbawahi bahwa pembagian manfaat dari kredit karbon harus sesuai dengan tanggung jawab semua orang.
Ruhiyat juga sepakat soal krusialnya aspek sosial dalam karbon integritas tinggi—di samping aspek teknis bahwa perhitungan pengurangan emisi harus menggunakan metode yang terkualifikasi dan bisa diverifikasi. Aspek sosial ini harus menjamin keterlibatan masyarakat dalam program pengurangan emisi dengan menginformasikan secara terbuka tujuan dari proyek itu serta apa manfaat dan kerugian bagi mereka apabila mereka ikut ataupun tidak ikut proyek tersebut. Ruhiyat menekankan, “Intinya, hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal itu harus kita tegakkan.”