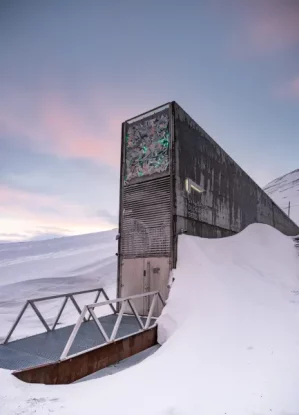Di tengah upaya dunia mengurangi emisi karbon, perhatian sering kali terfokus pada bahan bakar fosil dan perubahan tata guna lahan. Namun, di bawah perairan pesisir Indonesia terdapat aset berharga yang sangat besar namun kurang dimanfaatkan: hutan mangrove dan padang lamun, yang menjadi penyerap karbon terkuat di planet ini.
Dalam sebuah lokakarya “Nilai Ekonomi Karbon Biru dan Kepemimpinan Indonesia” yang digelar di Jakarta pada 14 Oktober 2025, para ilmuwan, pembuat kebijakan, dan pakar industri Indonesia berkumpul untuk membahas bagaimana Indonesia dapat menerjemahkan keunggulan ekologi ini menjadi peluang ekonomi dan memasukkannya ke dalam agenda karbon biru Indonesia, sebagai bagian dari keunggulannya di sektor kehutanan dan penggunaan lahan lain (forestry and other land use/FOLU).
Pesisir Indonesia menyimpan lebih dari sekadar keindahan alam — tapi juga menjadi salah satu penyimpan alami terkuat karbon di planet ini. Menurut Daniel Murdiyarso, ilmuwan utama di Center for International Forestry Research and World Agroforestry (CIFOR-ICRAF) dan ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), ekosistem mangrove dan lamun yang luas di negara ini memberikan keunggulan unik dalam potensi karbon biru. Indonesia memiliki sekitar seperempat hutan mangrove dan 15 persen padang lamun dunia, membentang di sepanjang pesisir negeri ini, salah satu negara dengan garis pantai terpanjang di bumi. Hutan mangrove negara ini mencakup luas sekitar 3,2 juta hektare. “Cadangan karbon [hutan mangrove negara ini] sekitar 3 miliar ton,” kata Daniel. “Kalau cadangan karbon 3 miliar ton ini dikonservasi, mestinya kita sama dengan menahan atau menunda emisi bahan bakar fosil.” Participants, speakers and guests gather for a group photo during the opening of the Blue Carbon Economic Value and Indonesia’s Leadership workshop at the National Library of Indonesia in Jakarta on 14 October 2025. The event brought together scientists, policymakers and practitioners to advance discussions on Indonesia’s blue carbon strategy and leadership in global carbon trading.
Konservasi: strategi iklim yang hemat biaya
Sayangnya, nilai ekonomi karbon dari konservasi mangrove masih sedikit dibicarakan. “Yang banyak dibicarakan adalah restorasi mangrove untuk menyerap karbon,” tutur Daniel. Padahal, biaya restorasi mangrove jauh lebih mahal dibanding biaya konservasinya. Sebuah studi dari Bank Dunia pada 2022 mengestimasi biaya rata-rata restorasi mangrove di Indonesia adalah sekitar 3.900 dolar AS per hektare.
“Dan upaya restorasi itu kadang-kadang gagal,” kata Daniel. “Sementara itu mengkonservasi jauh lebih rendah biayanya dan jasa lingkungannya jauh lebih besar sehingga benefit cost ratio-nya bisa 5 kali lebih besar dibanding benefit cost ratio restorasi mangrove. Jadi kalau mitigasi emisi cadangan minyak bisa diagendakan, pertanyaan kita hari ini, kenapa cadangan karbon biru di mangrove tidak bisa diperlakukan dengan cara yang sama?”
Membangun pasar karbon biru yang kredibel
Franky Zamzani, direktur Adaptasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup, mengatakan bahwa upaya konservasi dan restorasi karbon biru tidak hanya mendukung target pengurangan emisi gas rumah kaca Indonesia, tetapi juga memberikan manfaat tambahan — mulai dari “melestarikan keanekaragaman hayati, meningkatkan produktivitas perikanan, memperkuat ketahanan masyarakat pesisir, dan menciptakan peluang ekonomi baru yang berkeadilan.”
Franky meyakini membangun pasar yang kredibel adalah kunci untuk mengubah keunggulan Indonesia menjadi kepemimpinan ekonomi. “Indonesia dapat menjadi pelopor dalam mengembangkan ekonomi karbon global sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi upaya pengendalian perubahan iklim global,” ujar Franky. “Salah satu cara untuk mewujudkannya adalah dengan mengoptimalkan nilai ekonomi karbon negara ini.”
“Keunggulan kompetitif hanya dapat diwujudkan dengan membangun pasar karbon yang inklusif, didukung dengan infrastruktur yang transparan dan robust untuk menghasilkan kredit karbon berintegritas tinggi,” tegas Franky. “Masa depan perdagangan karbon di Indonesia akan ditentukan oleh kredibilitas dan integritas pasar karbon yang kita bangun dengan kredit karbon berintegritas dari masing-masing sektor.”
Hingga saat ini, Indonesia telah mendorong pengembangan multiskema dalam implementasi nilai ekonomi karbon termasuk melalui beberapa Perjanjian Pengakuan Bersama (Mutual Recognition Agreement/MRA) dengan lembaga-lembaga sertifikasi kredit karbon internasional seperti Verra dan Gold Standard. Perjanjian-perjanjian ini bertujuan untuk mengubah keunggulan komparatif Indonesia menjadi keunggulan kompetitif di pasar karbon internasional.
Namun, perubahan tersebut bergantung pada kredibilitas. Wahyudi Ali Adam, asisten direktur Divisi Pengawasan Bursa Karbon di Otoritas Jasa Keuangan, sepakat bahwa pasar karbon domestik Indonesia masih kurang dalam hal volume, kredibilitas, dan kepercayaan investor. “Kalau bicara nilai transaksi di Bursa Karbon Indonesia (IDX Carbon), dibandingkan dengan [nilai transaksi] saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), jelas jauh lebih kecil,” ujar Wahyudi. “Transaksi karbon tidak terjadi setiap hari. Transaksi saham harian bisa mencapai triliunan rupiah, sementara total transaksi karbon hingga saat ini hanya Rp78 miliar dari 1,6 juta ton karbon yang ditransaksikan.”
Di luar IDX Carbon, pemerintah Indonesia telah menjalin kemitraan perdagangan karbon bilateral — pertama dengan Norwegia dan kemudian dengan Jepang. Meskipun kerja sama dengan Norwegia sempat terhenti pada 2021 karena masalah teknis pembayaran, kerja sama tersebut kembali terjalin pada tahun 2022 dan kini makin diperkuat.
Sejak Januari 2025, Indonesia juga telah membuka IDX Carbon untuk pembeli internasional. Untuk pasar internasional, IDX Carbon menawarkan harga kredit karbon sebesar Rp96.000 (5,8 dolar AS) per ton di unit Indonesia Technology Based Solution (IDTBS) dan Rp144.000 (8,7 dolar AS) per ton di unit IDTBS Renewable Energy (IDTBS-RE). Harga karbon untuk pasar domestik lebih rendah lagi — rata-rata sekitar USD 4 per ton pada tahun 2023 dan kemudian sedikit turun pada akhir 2024.
Kepercayaan, integritas, dan inklusivitas
Aidy Halimanjaya, direktur Yayasan Transisi Berkeadilan, mengatakan bahwa kepercayaan sangatlah penting untuk menciptakan harga karbon yang kompetitif dan mendorong pembeli untuk berinvestasi dalam proyek karbon nasional. “Kepercayaan dibangun oleh proyek-proyek yang berkualitas,” ujarnya. “Tidak banyak proyek karbon di Indonesia. Jadi, kita perlu membuktikannya dengan seratus proyek pertama—yang clear dan clean—sehingga bisa membangun kepercayaan.”
Senada dengan pernyataan tersebut, Josi Katharina, peneliti senior Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), menekankan bahwa kepercayaan pembeli bergantung pada tata kelola yang kredibel dan integritas. “Yang sering disoroti oleh berbagai pemangku kepentingan adalah aspek integritas lingkungannya,” ujarnya. “Integritas lingkungan memastikan kita memiliki tata kelola dan sistem yang transparan dan sehat untuk memastikan hasilnya itu betul-betul berkontribusi secara faktual terhadap pengurangan emisi.”
“Definisi berintegritas ini yang harus kita terjemahkan ke tingkat tapak,” ujar Aji Wahyu Anggoro, blue carbon program manager di Yayasan Konservasi Alam Nusantara. Ia mengatakan masyarakat butuh peningkatan kapasitas untuk memahami nilai ekonomi karbon (NEK): apakah semua wilayah dapat memiliki NEK yang layak dijual, seberapa sulit mengukur dan menjual NEK, dan apa yang dimaksud dengan proyek karbon berintegritas tinggi. “Jadi, saya pikir memberikan pelatihan tentang hal ini penting agar ketika mereka berbicara tentang keadilan lingkungan dan mekanisme pendistribusian manfaat, mereka tahu apa hak mereka, berapa persentase manfaat yang seharusnya mereka terima, dan seperti apa bisnisnya.”
Di tingkat tapak, Hendro Supeno, ketua Kelompok Tani Hutan Makmur di Banyuwangi, Jawa Timur, menjelaskan bahwa kelompoknya telah melakukan restorasi dan konservasi mangrove di sepanjang pesisir wilayah mereka sejak tahun 1999. Hingga saat ini, kelompok tersebut telah merestorasi 1.600 hektare hutan mangrove. “Bagi masyarakat Banyuwangi, pemahaman soal karbon itu belum tersosialisasi dengan baik,” ungkap Hendro.
“Kami melakukan restorasi itu belum tahu soal nilai ekonomi karbon,” ujar Hendro. “Tanpa berkolaborasi dengan para akademisi, tentu kami tidak akan memahami apa itu karbon dan nilainya. Yang kami tahu restorasi hanya untuk perlindungan pesisir, perbaikan kualitas air, dan pencegahan abrasi.”
Participants attend the opening ceremony of the Blue Carbon Economic Value and Indonesia’s Leadership workshop at the National Library of Indonesia in Jakarta on 14 October 2025.
Lebih dari sekadar karbon: mata pencaharian dan ketahanan pangan
Mulia Nurhasan, ilmuwan CIFOR-ICRAF, berharap agar pendanaan dari perdagangan karbon bisa disalurkan ke masyarakat lokal yang sudah melakukan upaya konservasi mangrove. Penelitiannya menyoroti manfaat sosial yang lebih luas dari hutan mangrove yang dikonservasi. “Pertama, mangrove menyediakan sumber pendapatan yang inklusif namun terbatas,” ujarnya. “Dengan adanya hutan mangrove, siapa pun, termasuk perempuan, bisa memperoleh penghasilan dari menangkap ikan di sekitar pesisir, tanpa harus melaut jauh.”
Kedua, mangrove memainkan peran krusial dalam ketahanan pangan. Hasil riset lain yang Mulia kerjakan menunjukkan, rumah tangga pesisir Indonesia yang tinggal dekat hutan mangrove mengonsumsi 19–28 persen lebih banyak ikan segar dibanding rumah tangga pesisir lainnya. “Masyarakat pesisir yang tinggal di dekat area akuakultur, seperti tambak, hanya mengonsumsi ikan sekitar dua persen lebih banyak daripada wilayah pesisir lainnya,” katanya.
Nurhasan menekankan bahwa meskipun restorasi tetap penting, konservasi hutan mangrove yang ada harus menjadi prioritas. “Restorasi memang krusial, tetapi hutan mangrove yang ada itu jangan dirusak dan harus dikonservasi,” tegasnya. “Hutan mangrove bukan hanya penyerap karbon, melainkan juga sumber vital mata pencaharian yang inklusif dan produktif bagi masyarakat. Jika konservasi dan restorasi bisa berjalan beriringan, itu akan ideal.”