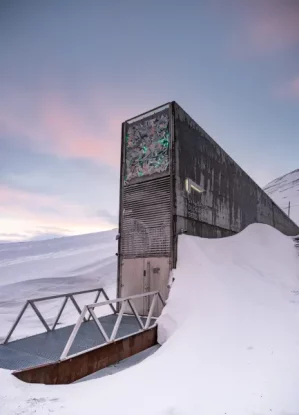Krisis kebakaran lahan dan gambut berskala besar telah mewarnai Asia Tenggara selama beberapa dekade, mengakibatkan asap lintas batas, pelepasan karbon tinggi, dan kerusakan area yang luas.
Sebagai upaya mengatasi masalah ini, ASEAN telah merumuskan sejumlah dokumen strategis, antara lain ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP), Peta Jalan Kerja Sama ASEAN menuju Pengendalian Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas Kedua 2023–2030, serta Strategi Pengelolaan Lahan Gambut ASEAN Kedua (APMS) 2023–2030. Dokumen-dokumen ini menjadi pedoman penting bagi inisiatif menuju kawasan bebas asap.
Kebakaran memang telah lama dimonitor dengan teknologi penginderaan jauh, tetapi pemetaan area terbakar yang lebih presisi dan seragam masih krusial untuk mendukung tata kelola kebakaran dan pemanfaatan lahan berkelanjutan. Saat ini, kawasan Asia Tenggara belum memiliki metode terpadu untuk pemetaan real-time yang dapat saling dibandingkan.
Kesenjangan tersebut akhirnya diisi dengan hadirnya Pedoman Pemetaan dan Estimasi Area Terbakar di Asia Tenggara yang perdana. Publikasi ini menyajikan panduan praktis bagi berbagai pemangku kepentingan—mulai dari pembuat kebijakan, peneliti hingga praktisi—untuk meningkatkan akurasi pemetaan dan pengelolaan kebakaran. Penyusunannya dipimpin CIFOR-ICRAF melalui proyek Measurable Action for Haze-Free Sustainable Land Management in Southeast Asia (MAHFSA) dengan dukungan negara anggota ASEAN, Sekretariat ASEAN, dan para ahli regional dari Indonesia, Thailand dan Lao PDR maupun internasional.
Kabar Hutan berkesempatan mewawancarai dua anggota tim penyusun pedoman — Michael Brady, peneliti senior CIFOR-ICRAF, dan Yenni Vetrita, peneliti senior BRIN — untuk menggali lebih dalam isi pedoman serta potensinya dalam memperkuat kapasitas pemangku kepentingan menghadapi kebakaran hutan di Asia Tenggara.
Tanya: Apa yang dimaksud dengan Pedoman Pemetaan dan Estimasi Area Terbakar di Asia Tenggara pertama, serta apa alasan di balik penyusunannya?
Michael Brady:Pedoman ini telah menjadi dokumen resmi ASEAN setelah disahkan oleh Committee under the Conference of the Parties to the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (COM AATHP). Dokumen ini ditujukan untuk membantu negara yang belum memulai pekerjaan serupa, sekaligus mendukung negara seperti Indonesia dalam pelatihan di tingkat provinsi maupun dalam berbagi pengalaman dengan negara tetangga.
Lebih dari sekadar panduan teknis, pedoman ini juga memberikan arahan membangun program nasional pemetaan area terbakar, lengkap dengan sumber daya dan data yang diperlukan untuk keberlanjutan.
Salah satu tantangan utama dalam pemetaan area terbakar adalah biaya tinggi, terutama karena membutuhkan verifikasi lapangan (ground truthing) di lokasi terpencil. Kini, sebagian verifikasi dapat digantikan dengan citra satelit beresolusi tinggi—kurang dari satu meter—yang mampu memperlihatkan tanda kebakaran seperti vegetasi hangus, abu, asap, bahkan api, tanpa harus turun langsung ke lapangan.
Inovasi ini telah memangkas biaya verifikasi dan validasi serta menyusun prosesnya secara lebih rapi. Walau terkesan teknis, hal ini merupakan pencapaian besar yang membuat pemetaan area terbakar semakin terjangkau dan dapat diandalkan di kawasan Asia Tenggara.
Yenni Vetrita:Pentingnya pemetaan dan estimasi area terbakar di Asia Tenggara tak lepas dari besarnya dampak kebakaran, pengalaman yang nyata dirasakan di Indonesia. Pemetaan berfungsi bukan hanya menunjukkan titik kebakaran, melainkan juga mendukung perhitungan kerugian dan emisi, terutama dari lahan gambut.
Tantangan pemantauan kebakaran di Asia Tenggara muncul karena perbedaan skala dan tujuan, mulai dari kebakaran hutan luas hingga pembakaran kecil terkontrol. Ditambah lagi, faktor seperti tutupan awan, akses terbatas, dan beragamnya penggunaan lahan membuat pemantauan berbasis darat sulit dijalankan dengan efektif.
Pendekatan berbasis satelit menawarkan solusi penting dengan menyediakan pemantauan yang konsisten, real-time, dan mencakup wilayah luas—mendukung tindakan cepat terhadap kebakaran, estimasi emisi, serta pengelolaan lahan berkelanjutan di Asia Tenggara.
Tanya: Bagaimana panduan ini membantu mengelola dan mengurangi dampak kebakaran hutan?
Yenni Vetrita:Pedoman ini membantu negara-negara di Asia Tenggara mengelola dan mengurangi dampak kebakaran hutan dengan menyediakan cara yang jelas dan konsisten untuk memetakan serta melaporkan area terbakar. Lebih lanjut, pedoman ditujukan untuk berbagai pihak, mulai dari pembuat kebijakan (seperti kementerian kehutanan dan lingkungan), pengelola lahan, hingga peneliti, sehingga data yang dihasilkan bisa langsung digunakan untuk mendorong aksi nyata di lapangan.
Konsistensi ini membantu respons yang lebih cepat, perencanaan yang lebih baik, dan perkiraan kerugian serta emisi yang lebih akurat, suatu hal penting bagi wilayah rawan kebakaran seperti Indonesia. Panduan ini juga mendorong pelaporan yang seragam, sehingga data bisa dimanfaatkan tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional, termasuk untuk menangani masalah asap lintas batas.
Michael Brady:Salah satu alasan kami ingin memperkenalkan metodologi ini adalah karena selama 30 tahun terakhir, sejak kebakaran besar di wilayah selatan Asia Tenggara, deteksi kebakaran sebagian besar masih mengandalkan hot spot. Hot spot ini terdeteksi secara termal melalui citra satelit, artinya satelit menandai sebuah hot spot ketika suhu pada satu piksel melewati ambang batas tertentu, yang diasumsikan menandakan adanya kebakaran.
Namun, cara tersebut merupakan pengukuran tidak langsung dan tidak memberikan informasi yang cukup mengenai luas area terbakar maupun ukuran dan tingkat keparahan kebakaran.
Sementara itu, pemetaan area terbakar memungkinkan kita untuk mengukur berapa hektare yang terbakar pada berbagai skala, sehingga kita bisa mengetahui total luas area terbakar setiap tahun di tingkat nasional.
Setelah mengetahui seberapa luas area yang terbakar, kita juga bisa menilai jenis tutupan lahan atau bahan bakar yang terbakar misalnya hutan atau padang rumput dengan menggabungkannya dengan data lain. Hal ini membuka peluang untuk analisis tambahan yang lebih mendalam.
FN: Siapa yang menjadi sasaran penerapan pedoman ini, dan bagaimana pedoman ini dirancang untuk mengatasi tantangan khusus di Asia Tenggara?
Yenni Vetrita:Pedoman ini terutama dirancang untuk digunakan di kawasan ASEAN, dengan mengacu pada penerapannya di Indonesia dan Thailand, di mana upaya pemetaan area terbakar di tingkat nasional dan subnasional sudah mulai dilakukan.
Kebakaran hutan di Asia Tenggara memang punya tantangan tersendiri mulai dari tutupan awan yang hampir selalu ada, kebakaran kecil yang tersebar dan sering terkait dengan praktik penggunaan lahan (misalnya untuk pertanian), hingga berbagai jenis kebakaran, seperti kebakaran lahan kering di Thailand dan kebakaran gambut di Indonesia. Kondisi ini membuat pemantauan langsung di lapangan menjadi sulit dan kurang efektif.
Yang membuat pedoman ini sangat relevan adalah fleksibilitasnya. Pedoman ini mendorong pemanfaatan data satelit gratis seperti Landsat dan Sentinel-2, merekomendasikan penggunaan citra radar untuk mengatasi masalah tutupan awan, serta mendukung metode manual maupun otomatis sesuai dengan kemampuan dan sumber daya lokal. Panduan ini bukan model yang sama untuk semua, melainkan dapat disesuaikan dengan kompleksitas masing-masing kawasan.
Michael Brady:Negara-negara seperti Indonesia telah melakukan pemetaan area terbakar, sementara negara lain seperti Malaysia dan Thailand juga mulai menggunakan metode serupa, meski penerapannya belum rutin dan operasional. Kami sangat ingin mendukung mereka agar dapat mencapai tahap tersebut. Namun, ada beberapa negara yang sama sekali belum melakukan pemetaan sendiri dan masih bergantung pada produk pemetaan area terbakar global. Produk global ini memang berguna untuk penilaian skala besar, tetapi terlalu kasar dan kurang efektif untuk digunakan di tingkat nasional maupun subnasional.
Kami sangat menyarankan agar setiap negara mulai membuat peta area terbakar mereka sendiri. Secara teknis, proses ini tidak terlalu rumit. Dalam pedoman ini, kami menyertakan bab tentang pengendalian kualitas dan validasi, suatu langkah lanjutan yang penting, namun pemetaan dasar sebenarnya cukup mudah dilakukan. Sebagian besar negara sudah memiliki tenaga ahli penginderaan jauh yang terlatih untuk melaksanakan hal ini; sering kali yang masih kurang adalah mandat atau program terstruktur di lembaga mereka untuk memproduksi peta ini secara rutin.
Tanya: Mengapa penting memiliki metode yang konsisten untuk memetakan area terbakar di berbagai negara di Asia Tenggara?
Michael Brady:Salah satu alasan awal kami mengembangkan pedoman ini adalah pengalaman dengan hot spot, di mana setiap yurisdiksi menggunakan ambang suhu yang berbeda-beda, sehingga jumlah kebakaran yang dihitung sering diragukan. Dengan pemetaan area terbakar, tujuannya adalah memulai dari awal dan mendorong pendekatan yang lebih seragam. ASEAN merupakan organisasi kawasan yang relatif terkoordinasi dengan baik; jika sebuah pedoman disahkan di tingkat ASEAN, kemungkinan besar pedoman tersebut akan diadopsi dan diterapkan.
Hal ini menjadi dorongan kuat untuk mengembangkan pendekatan yang disepakati bersama. Tujuan utamanya adalah mendukung negara-negara menghasilkan data luas area terbakar tahunan di tingkat nasional yang kredibel. Hal ini penting, tidak hanya untuk pengelolaan kebakaran secara operasional, tetapi juga ketika data tersebut digunakan untuk perhitungan karbon atau pelaporan emisi gas rumah kaca nasional. Dengan metode yang seragam, data yang dihasilkan menjadi konsisten, dapat dibandingkan, dan dapat dipertanggungjawabkan di seluruh kawasan.
Tanya: Bagaimana pedoman ini disosialisasikan dan diterapkan di berbagai wilayah serta oleh beragam pemangku kepentingan?
Michael Brady:Penyusunan panduan ini memakan waktu lebih dari dua tahun dan melibatkan lokakarya dengan semua negara ASEAN serta sejumlah pakar internasional. Isinya dibahas, direvisi, dan akhirnya disahkan oleh perwakilan ASEAN.
Saat ini, panduan ini sudah tersedia di situs web ASEAN. Promosi dan pemanfaatannya menjadi tanggung jawab utama Sekretariat ASEAN, meskipun CIFOR juga akan membagikannya melalui jaringan kami dan mendukung pelatihan bila diperlukan. Ke depannya, kami mendorong setiap negara untuk memimpin sendiri pelatihan dan penerapannya.
Yenni Vetrita:Pelatihan dan lokakarya di tingkat pemerintah daerah sangat penting. Di Indonesia, kami aktif melibatkan otoritas lokal dan mengajarkan mereka cara menerapkan teknik ini. Pendekatan ini memastikan informasi penting terkait kebakaran dapat dikumpulkan lebih dekat dengan sumbernya, sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan efektif. Ketika tim lokal dibekali dengan alat dan pengetahuan yang tepat, pengelolaan kebakaran menjadi lebih responsif, terkoordinasi, dan pada akhirnya lebih berdampak.
Tanya: Apakah ada kesimpulan atau pendapat terakhir?
Yenni Vetrita:Pemetaan area terbakar di negara yang luas dan beragam seperti Indonesia tidak pernah mudah. Pola kebakaran sangat bervariasi dari satu wilayah ke wilayah lain, namun sejak awal kami menyadari bahwa pemetaan yang konsisten dan andal sangat penting.
Kami baru-baru ini menerbitkan artikel ilmiah yang menjelaskan teknik kami. Metode ini mungkin terlihat sederhana bagi sebagian orang, tetapi relatif mudah diterapkan, bahkan bagi negara yang belum pernah melakukan pemetaan area terbakar sebelumnya. Indonesia belajar melalui praktik langsung.
Seiring waktu, kami menyempurnakan proses, mendokumentasikannya, dan mengembangkannya menjadi prosedur yang terstandarisasi. Memiliki standar yang jelas seperti diuraikan dalam panduan ini, telah meningkatkan kepercayaan diri kami. Tidak ada metode yang sempurna; selalu ada keterbatasan, baik dari sisi data, alat, maupun metode. Namun, pendekatan yang transparan dan dapat direplikasi memberikan dasar yang kuat untuk dijadikan acuan.
Yang tidak kalah penting adalah penyebarluasan pengetahuan ini. Pelatihan dan pertukaran harus dilakukan tidak hanya antarnegara, tetapi juga dengan pemerintah daerah dan komunitas. Indonesia secara aktif memperluas kapasitas di tingkat lokal, karena kami percaya bahwa membangun keterampilan di semua lapisan — tidak hanya di lembaga pusat — akan meningkatkan kesadaran, memperkuat sistem peringatan dini, dan meningkatkan kesiapsiagaan regional.
Profil para ahli
Michael Brady adalah Senior Associate di CIFOR-ICRAF, Bogor. Sejak 1985, ia meneliti perilaku kebakaran hutan di Asia Tenggara dan aktif terlibat dalam pemantauan serta upaya mitigasi kebakaran di tingkat global. Pada 1999, ia memperkenalkan sistem penilaian bahaya kebakaran (fire danger rating) di kawasan ini. Di awal 2000-an, ia juga memimpin pemetaan tahunan area terbakar di Kanada.
Yenni Vetrita adalah peneliti senior di BRIN yang sejak 2005 fokus pada penggunaan penginderaan jauh untuk mempelajari kebakaran hutan tropis, pemantauan lingkungan, dan manajemen bencana, khususnya di ekosistem gambut dan hutan Indonesia. Ia juga menjadi National Focal Point Indonesia untuk UN-SPIDER Regional Support Office, dan mendorong pemanfaatan informasi berbasis antariksa dalam manajemen bencana.
Ucapan terima kasih
Blog tanya jawab ini disusun dengan dukungan program Measurable Action for Haze-Free Southeast Asia (MAHFSA). MAHFSA merupakan inisiatif bersama ASEAN dan International Fund for Agricultural Development (IFAD) yang mendukung upaya mengurangi polusi asap lintas batas dan dampaknya di Asia Tenggara.
Blog ini dapat terwujud berkat dukungan Divisi Lingkungan Sekretariat ASEAN, serta kontribusi para ahli.